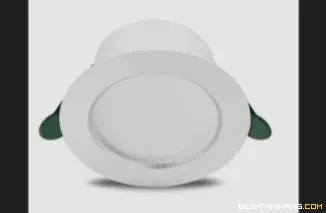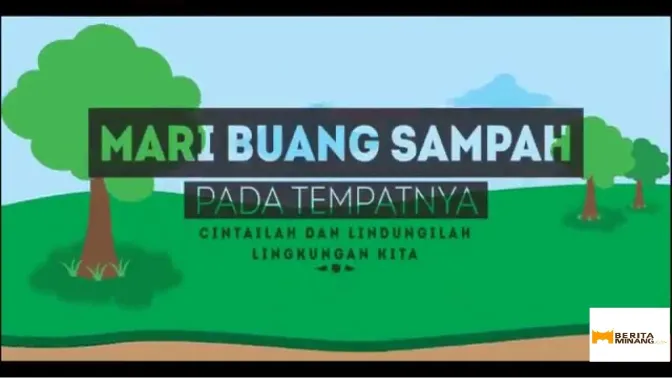BEBERAPA waktu lalu, jalanan kota besar di Indonesia kembali ramai. Ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat tumpah ruah ke jalan menolak kebijakan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang dianggap berlebihan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Demo 2025 ini tak hanya mengguncang gedung parlemen, tapi juga dunia maya. Tagar #SaveKPK yang dulu pernah viral kini berganti wajah menjadi #TolakPrivilegiDPR, menghiasi linimasa X, Instagram, dan TikTok. Video orasi, kericuhan, hingga tangisan ibu-ibu di depan pagar DPR tersebar dalam hitungan menit. Di balik hiruk pikuk itu, satu hal tampak jelas: politik Indonesia kini tidak lagi hanya hidup di jalanan, tapi juga di layar ponsel.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana digitalisasi mengubah wajah partisipasi politik. Dulu, partisipasi politik dipahami sebatas kegiatan konvensional seperti mencoblos saat pemilu, bergabung dengan partai, atau ikut aksi massa. Namun, teori digital political participation memperluas konsep itu. Menurut Pippa Norris (2001), digitalisasi membuka ruang baru bagi warga untuk terlibat dalam proses politik melalui aktivitas online yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Jensen dan van Dijk (2013) menambahkan bahwa media digital memungkinkan warga untuk berpartisipasi tanpa harus melalui lembaga formal, menciptakan bentuk keterlibatan baru yang lebih personal, cepat, dan spontan.
Demo 2025 menjadi bukti konkret dari teori ini. Media sosial berfungsi sebagai katalis yang mengubah percakapan online menjadi mobilisasi nyata. Tagar yang awalnya hanya berupa teks akhirnya mampu menggerakkan ribuan orang turun ke jalan. Namun, perubahan cepat ini juga menghadirkan dilema baru. Di tengah derasnya arus informasi, kecepatan sering kali mengalahkan keakuratan. Salah satu contoh yang sempat ramai adalah kabar bahwa seorang pengemudi ojek online tewas karena membantu massa. Belakangan, fakta menunjukkan bahwa ia hanyalah korban kebetulan yang sedang mengantar pesanan di sekitar lokasi demo. Kejadian ini memperlihatkan bahwa partisipasi digital dapat menjadi pisau bermata dua: bisa memperkuat solidaritas sosial, tapi juga bisa menyulut kesalahpahaman massal.
Yang menarik, setelah gelombang aksi itu, sejumlah pengguna melaporkan bahwa fitur siaran langsung di TikTok mendadak sulit diakses. Tidak ada penjelasan resmi, tapi banyak yang mengaitkannya dengan maraknya siaran demo di berbagai kota. Apakah ini kebetulan teknis atau bentuk kontrol terhadap arus informasi? Pertanyaan itu tetap menggantung. Di titik inilah teori digital participation kembali relevan: ruang digital memang demokratis, tapi juga tidak sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasaan. Teknologi memberi kebebasan, tetapi juga menyediakan instrumen baru bagi kontrol sosial.
Generasi muda menjadi aktor paling dominan dalam perubahan ini. Mereka bukan hanya konsumen informasi, melainkan produsen wacana politik. Dengan memanfaatkan algoritma dan tren media sosial, mereka mampu membentuk opini publik lebih cepat daripada media arus utama. Namun, seperti yang dijelaskan oleh van Dijk, partisipasi digital sering kali bersifat "fragmentaris" dan "superfisial". Banyak yang ikut menyuarakan isu bukan karena kesadaran politik, melainkan karena tekanan sosial atau sekadar mengikuti tren. Aktivisme pun berubah menjadi performa sosial, di mana keberpihakan politik kadang hanya sejauh postingan story atau unggahan tagar.
Partisipasi politik di era digital pada akhirnya menuntut keseimbangan antara semangat dan kesadaran. Semangat untuk terus bersuara, dan kesadaran untuk tetap kritis terhadap setiap informasi yang beredar. Demokrasi digital tidak cukup hanya dengan koneksi internet dan keberanian berkomentar, tetapi juga membutuhkan kemampuan berpikir jernih, empati sosial, dan tanggung jawab moral. Demo 2025 menunjukkan betapa besar pengaruh teknologi dalam menggerakkan partisipasi, tapi juga betapa mudahnya kebenaran tergelincir di tengah arus viralitas.
Kini kita hidup di masa di mana politik dan algoritma saling bertaut. Dunia digital bukan lagi sekadar ruang tambahan, tetapi panggung utama tempat demokrasi kita sedang diuji. Mungkin sudah waktunya bagi generasi muda untuk berhenti sekadar menjadi “penonton” politik digital dan mulai mengambil peran sebagai warga yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab atas suaranya — baik di dunia nyata maupun di dunia maya. (***)