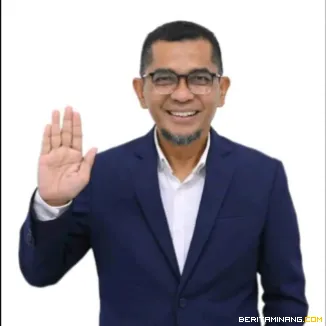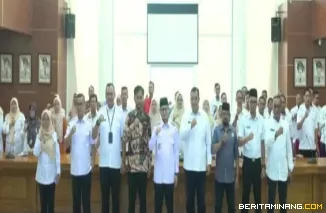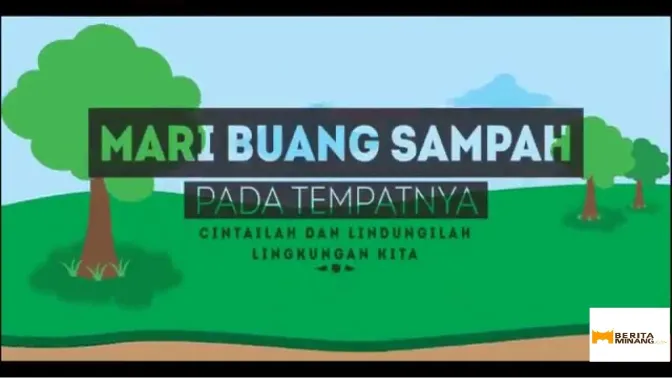Michel Foucault pernah menegaskan bahwa “kekuasaan itu hadir di mana-mana, merembes dalam relasi sosial, dan sering kali bekerja melalui institusi yang dianggap netral.” Dalam konteks Indonesia, Polri adalah representasi nyata dari teori itu. Ia bukan hanya penegak hukum, tetapi instrumen kuasa yang menentukan siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus dibungkam.
Masalah besar lain yang dihadapi Polri adalah krisis kepercayaan publik. Survei demi survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri cenderung fluktuatif, bahkan sering jatuh akibat kasus-kasus besar, seperti korupsi di tubuh kepolisian, kasus pembunuhan yang melibatkan aparat, hingga keterlibatan dalam praktik mafia hukum.
Legitimasi publik adalah fondasi utama bagi sebuah institusi penegak hukum. Tanpa legitimasi, setiap kebijakan Polri akan dipandang sebagai instrumen represi, bukan perlindungan. Inilah titik krusial yang harus dijawab oleh Kapolri: bagaimana mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi nyata, bukan sekadar retorika?
Bisakah Paradigma Itu Diubah?
Pertanyaan paling mendasar adalah: bisakah Polri benar-benar mengubah paradigma kekuasaan yang sudah mengakar? Jawabannya tentu tidak sederhana. Reformasi institusional selalu menghadapi resistensi dari dalam. Budaya kekuasaan yang sudah tertanam puluhan tahun tidak bisa dibongkar hanya dengan slogan atau peraturan baru.
Namun, bukan berarti perubahan mustahil. Polri bisa memulai dengan tiga langkah:
2. Reformasi kultural membongkar budaya kekerasan, mengganti paradigma represif dengan paradigma pelayanan publik.
3. Reformasi hukum menegakkan prinsip equality before the law tanpa pandang bulu, baik terhadap rakyat kecil maupun pejabat tinggi.
Ketiga langkah ini membutuhkan kepemimpinan Kapolri yang visioner, berani, dan berkomitmen pada demokrasi. Tanpa itu, Polri hanya akan menjadi institusi yang sibuk mempercantik citra, sementara rakyat tetap tercekik dalam sistem hukum yang timpang.